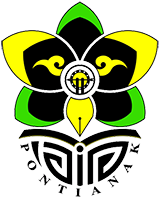Oleh : Eka Hendry Ar.
Dosen Studi Agama-agama FUAD IAIN Pontianak
Semiotika dan kopi, adalah dua istilah yang akhir-akhir ini memenuhi ruang diskusi penulis. Semiotika adalah pecahan dari linguistik yang berbicara tentang makna simbolik, sedangkan kopi adalah diksi yang bisa dalam artian denotatif maupun konotatif. Secara denotatif adalah jenis minuman populer, dari biji kopi yang ditumbuk halus menjadi serbuk. Kemudian diseduh dengan air panas, dengan gula (atau tanpa gula) nikmat diserput dalam keadaan hangat. Sedangkan konotasinya, “Ngopi”, merupakan kegiatan kongko-kongko entah itu di warung kopi atau cafe (istilah milennialnya). Belum tentu minum kopi, bisa saja minum teh, minum susu, jus, atau sarapan makanan-makanan ringan, tapi aktivitas ini disebut Ngopi.
Kalau dua istilah ini disepadankan, kira-kira kemana arah perbincangannya. Konteksnya adalah bagaimana membaca fenomena Kopi, Ngopi dalam tinjauan semiotika. Karena Kopi (kata benda), ngopi (kata kerja) merupakan objek, sedangkan semiotika lebih sebagai pendekatan atau instrumen untuk membedah fenomena objek. Dalam pandangan semiotika, setiap aktivitas manusia akan menciptakan simbol-simbol (baik diksi, gambar, tindakan dan sikap) yang mengandung maksud yang lebih dalam dari sekedar bahasa verbalistik denotatif. Biasanya melalui lambang (dan termasuk simbol) manusia lebih leluasa memuat nilai-nilai yang diyakini, pandangan dunia (weltanschaung) dan tujuannya (telos).
Demikian halnya dengan fenomena Ngopi (dan semua atributnya), juga merupakan lambang-lambang (the signs) yang memiliki makna simbolik, mulai dari diksi, objek dan tempat (spacial) dan waktu (temporal). Makna ini tidak akan dimengerti kalau hanya sekedar melihat realitas empirisnya, akan tetapi perlu diselami secara mendalam.
Berdasarkan pengamatan dan telaah penulis, setelah lebih dari 6 tahun menjadi penikmat warung kopi. Ada beberapa fenomena yang penulis potret dari Kopi dan Ngopi:
Pertama, Minum kopi, sekarang bukan hanya kebiasaan (habitual), akan tetapi sudah menjadi gaya hidup (life style) atau budaya. Dahulu yang datang ke warung kopi, lebih dominan pria dewasa (dan orang tua) yang datang untuk ketemu teman, bicara tentang banyak hal atau curhat (tentang keluarga, kondisi sosial politik, termasuk pekerjaan), sambil menyeruput kopi panas gelas kecil dengan berbagai cemilan kampung. Jarang anak-anak muda, apalagi perempuan datang dan duduk di warung kopi. Tapi dalam 1, 2 dasawarsa terakhir, trendnya mulai berubah. Menjamur warung-warung kopi, dan sekarang bermetamorfosa menjadi cafe-cafe, dan didatangi oleh para anak muda, remaja, keluarga (baik kalangan pria dan wanita). Fenomena ini penulis sebut sebagai transformasi dari kebiasaan menjadi life style. Ada prestige sendiri bahwa, kopi adalah “ruang santai”, tempat relaksasi, tempat bersosialisasi, tempat informal (tapi serius), ini menjadi semacam pranata alternatif (alternative institution) di samping berbagai formal lainnya. Konsep prestige ini juga berkonotasi dengan rasa egaliter, rasa gaul, rasa berkelas, orang perkotaan (kosmopolitan).
Kedua, transformasi fungsi, apakah ini terjadi. Mungkin tidak sepenuhnya baru, karena penulis meyakini dari segi fungsi Ngopi dan Warung Kopi, relatif sama. Warung kopi memiliki fungsi ruang publik selaku media pertemuan dalam suasana informal dan menyenangkan. Konsep konservatif ini hemat penulis masih menjadi ruh yang sama dari Kopi dan Warung Kopi. Namun demikian, berdasarkan pengamatan penulis ada diversifikasi dalam konteks subjek, kepentingan, diskursus dan suasana kebatinannya. Subjek yang datang lebih variatif (baik dari segi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial dlsb). Kemudian dari segi kepentingan juga lebih variatif (tidak hanya berkenaan dengan pekerjaan, tetapi juga tugas kuliah, transaksi bisnis, atau jusf for fun). Sedangkan wacana atau diskursus yang dibincangkan juga variatif, mulai dari persoalan pribadi, pekerjaan, perkuliahan, isu politik aktual hingga persoalan keagamaan. Pernah satu waktu, penulis menyimak perbincangan beberapa pemuda, kalau dari segi tampilan seperti freeman (urak-urakan). Ternyata yang diperbincangkan adalah tentang konsep tasawuf yang sulit dipahami. Dan variasi juga terjadi dalam suasana kebatinan yang berbeda. Suasana kebatinan antara berkumpul dengan orang yang relatif homogen, dengan orang-orang yang relatif heterogen. Aspek ruang (spacial) dengan background suggestopedia Gregory Lazanov misalnya, sugesti isntrumental alamiah atau musik dengan nada slow, dengan maksud menciptakan suasana rileks dan natural. Berbeda dengan warung kopi konvensional (atau tradisional) yang tidak mementingkan penciptaan sugesti spacial (baik gambar dan sound effect).
Ketiga, Warung kopi (cafe) selain sebagai ruang publik (meminjam Jurgen Habermas), juga sekarang sekarang sebagai ruang semiotika tentang gaya hidup, egalitarian, anti kemapanan, dan pandangan dunia kosmopolit, dan inklusifitas. Menurut Habermas, ruang publik adalah ruang yang menjembatani antara negara (aktor negara) dengan masyarakat sipil (masyarakat). Ruang publik sebagai ruang universal, tempat orang-orang berkumpul dan mendiskusikan banyak hal. Konsep Habermas diinterpretasi dalam konteks demokrasi sebagai demokrasi deliberatif, yaitu masyarakat punya ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks kontemporer, semiotika warung kopi (cafe) menjadi semacam ruang fashion show bagi ekspresi gaya hidup masyarakat urban, yang gaul, santai dan egaliter. Semiotika anti kemapanan atau melawan mainstream, karena spacial cafe atau warung kopi tidak sebenarnya termasuk longar norma, hanya norma umum saja yang berlaku. Longgar norma seperti tidak ada keharusan waktu, pakaian yang seharusnya, pilihan tempat duduknya tidak ada kasta, jenis makanan tidak merepresentasikan kelas atau segmen sosial tertentu. Berbeda kalau kita harus pergi ke restoran mahal, atau restoran hotel, harus pada jam tertentu, kadang perlu reservasi tempat, kadang dituntut untuk menggunakan pakaian yang pantas serta berbagai aturan table manner. Konsekwensi dari situasi seperti ini, berimbas kepada mindset dan bertindak, menjadi lebih santas, tanpa beban, masuk ke dalam relaksasi, egalitaran dan perasaan nyaman (comfortable). Dan yang tak kalah penting, spacial cafe atau warung kopi menjadi ruang inklusif bagi keragaman, karena setiap orang tidak terlalu memperdulikan latar belakang status sosial, biologis, politik dan bahkan agama satu sama lain. Semuanya merasa menjadi “warga cafe/warung kopi”, membangun keakraban meski tidak saling berkomunikasi verbal, tapi membangun komunikasi non verbal, seperti berbagi meja, berbagi kursi, berbagi pengertian kalau ada yang lama menunggu belum mendapatkan tempat duduk, menjadi toleran untuk tidak berbicara dan tertawa yang bisa menganggu orang lain. Jadi ada semacam toleransi diam (silent tolerance) yang terbangun diantara sesama “warga cafe/warung kopi”. Datang dan pergi silih berganti, datang tidak mengganggu yang ada, pergi bukan karena merasa terusir dengan kehadiran yang lain. Ini kira-kira kalimat yang pas untuk mengambarkan cerminan egaliterian warga cafe atau warung kopi.
Beda ruang publik Habermas dengan fenemena warga cafe/warung kopi, tidak adanya keharusan bahwa, ruang publik harus menjadi ruang kritik terhadap pemerintah. Karena dalam pandangan Habermas, jika tidak ada fungsi kritik, maka ini menjadi semacam “penghianatan” intelektual dari warga ruang publik. Sedangkan dalam konteks warga cafe/warung kopi, ruang publik adalah ruang lalu lintas sosialisasi, lalu lintas wacana, perlintasan segmentasi, namun tidak ada dosa atau “penghianatan” jika warganya tidak membuat keputusan atau kritik terhadap kebijakan publik pemerintah. Makanya, warga cafe/warung kopi kontemporer menjadi sangat rekat “perselingkuhannya” dengan kekuasaan, alias berdamai.
Keempat, telah terjadi liberalisasi ruang publik Warung Kopi, bukan lagi sebagai ruang ideologis. Ruang Warung Kopi sekarang betul-betul menjelma sebagai ruang bebas bagi kapitalisasi (untuk tidak menyebut kapitalisme). Ideologi warung kopi terdegradasi sebagai kegiatan pure business, pure entertainment, pure joyfull, meski ada juga aktivitas freely learning (belajar secara bebas). Jadi harapan Jurgen ruang publik menjadi “ruang kritis” berubah menjadi “ruang pragmatis”.
Berdasarkan telaah semiotik di atas, penulis sampai kepada kesimpulan bahwa, pragmatisme sedang melanda ruang publik “Warung Kopi”. Ada degradasi ideologis fungsi ruang publik seperti diharapkan Jurgen Habermas, pada satu sisi. Sementara di sisi lain, yang menggembirakan dari ruang publik kini, yaitu mengalami diversifikasi fungsi dan formula, menjadi lebih kreatif dan memanifestasikan kebutuhan hidup masyarakat kontemporer. Trend ini sepertinya akan panjang, seiring dengan semakin kuatnya budaya santai (relaxed culture) di tengah sumpeknya rutinitas formal yang “membosankan” melanda masyarakat kita. ***